Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber daya alam: hutan tropis, lautan luas, dan keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Namun di balik kekayaan itu, tersimpan tantangan besar dalam menjaga keseimbangannya.

Perjalanan Undang-Undang Lingkungan Hidup di Indonesia menjadi cermin bagaimana negara ini berusaha menata hubungan antara pembangunan dan pelestarian alam.
Sebagaimana dijelaskan dalam laman https://dlhpadangpariaman.org/, upaya menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga seluruh elemen masyarakat. Dari sinilah kita belajar bahwa hukum bukan sekadar aturan, tetapi kompas moral untuk merawat bumi.
Awal Mula: UU 4 Tahun 1982
Cikal bakal hukum lingkungan modern di Indonesia dimulai dengan UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini lahir setelah dunia mulai sadar akan pentingnya keseimbangan ekosistem pasca Konferensi Stockholm 1972.
Untuk pertama kalinya, negara mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Di masa itu, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Hutan ditebang, tambang dibuka, dan sungai tercemar atas nama kemajuan.
Meski sederhana, UU 4/1982 telah membuka jalan bagi kesadaran bahwa kemajuan sejati tak bisa dipisahkan dari kelestarian lingkungan.
Era 1997: Meningkatkan Partisipasi Publik
Memasuki akhir abad ke-20, Indonesia memperbarui regulasinya dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU ini, istilah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) diperkenalkan secara resmi. Masyarakat pun diberi hak untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan di sekitarnya.
Langkah ini penting, karena menunjukkan bahwa pelestarian alam bukan hanya urusan politik, pejabat atau ahli, tetapi juga warga biasa.
Sayangnya, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat banyak kasus pencemaran tetap lolos dari jerat hukum. Namun begitu, UU 23/1997 tetap menjadi tonggak penting menuju keterlibatan publik yang lebih luas dalam isu-isu lingkungan.
UU 32 Tahun 2009: Perlindungan dan Pengelolaan
Tahun 2009 menjadi momentum besar bagi hukum lingkungan Indonesia dengan lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Inilah regulasi paling komprehensif hingga kini.
UU ini tidak hanya berbicara soal pengelolaan, tetapi juga perlindungan. Salah satu pasalnya yang paling terkenal adalah Pasal 66, yang menyatakan:
“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”
Pasal ini menjadi dasar bagi aktivis dan masyarakat untuk terus bersuara tanpa takut kriminalisasi. Namun dalam kenyataannya, masih banyak pejuang lingkungan yang mendapat tekanan. Ini menandakan bahwa pelaksanaan UU seringkali belum sekuat semangat yang tertulis di dalamnya.
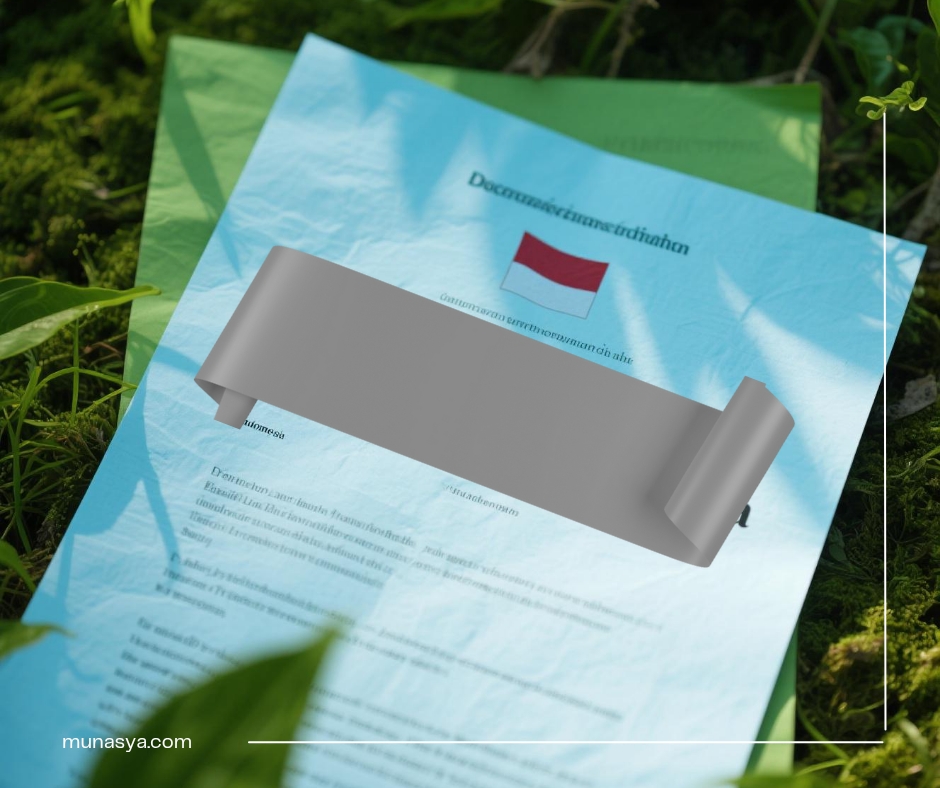
Era Deregulasi: Lahirnya UU Cipta Kerja
Tahun 2020, Indonesia memasuki era baru dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini membawa banyak perubahan, termasuk terhadap UU 32/2009. Salah satu yang paling menonjol adalah penghapusan “izin lingkungan” dan digantikan dengan istilah “persetujuan lingkungan.”
Pemerintah beralasan bahwa hal ini untuk mempermudah investasi dan mempercepat proses perizinan. Namun, sejumlah pakar menilai bahwa langkah ini bisa melemahkan kontrol masyarakat terhadap kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan.
Muncullah dilema klasik: pembangunan ekonomi vs pelestarian lingkungan. Meski begitu, pemerintah tetap menegaskan bahwa prinsip perlindungan lingkungan tidak dihapus, hanya tata kelolanya yang disesuaikan.
UU 32 Tahun 2024: Menyongsong Konservasi Baru
Perjalanan hukum lingkungan belum berhenti. Tahun 2024, Indonesia kembali memperbarui regulasinya melalui UU Nomor 32 Tahun 2024 yang merevisi UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Revisi ini memperkuat tiga pilar utama:
- Perlindungan sistem penyangga kehidupan,
- Pengawetan keanekaragaman hayati, dan
- Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.
UU terbaru ini menekankan konservasi di tingkat tapak, yakni pengelolaan langsung oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga lokal. Inilah bentuk desentralisasi perlindungan alam agar lebih dekat dengan masyarakat.
Seperti yang juga dipaparkan dalam laman https://dlhpadangpariaman.org/, keberhasilan pelestarian lingkungan sangat bergantung pada kolaborasi antara regulasi, masyarakat, dan kesadaran lokal.
Penegakan Hukum: Masalah Lama yang Belum Tuntas
Meskipun regulasi terus diperbarui, penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kasus pencemaran sungai, kebakaran hutan, hingga kerusakan mangrove seringkali tidak berujung pada hukuman yang setimpal.
Mahkamah Konstitusi sempat mempertegas bahwa aktivis lingkungan harus dilindungi hukum, bukan dikriminalisasi. Putusan MK tahun 2025 bahkan menegaskan kembali makna Pasal 66 UU 32/2009 sebagai bentuk perlindungan bagi pembela lingkungan. Namun, hukum tidak akan berarti tanpa kesadaran kolektif masyarakat.
Ketika warga ikut mengawasi, melaporkan, dan menolak praktik pencemaran, di situlah hukum lingkungan benar-benar hidup.
Jejak panjang UU Lingkungan Hidup di Indonesia menggambarkan perjalanan panjang bangsa dalam menata hubungan antara manusia dan alam. Dari UU 4/1982 hingga UU 32/2024, setiap perubahan membawa semangat baru untuk menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian.
Namun, tanggung jawab terbesar tetap berada di tangan kita semua, masyarakat yang setiap harinya hidup dan bergantung pada alam. Karena hukum sekuat apa pun tak akan bermakna tanpa tindakan nyata dari warganya.“Bumi bukan warisan dari leluhur, melainkan titipan dari anak cucu yang harus kita jaga.




